Perdebatan Nasab Anak di Indonesia
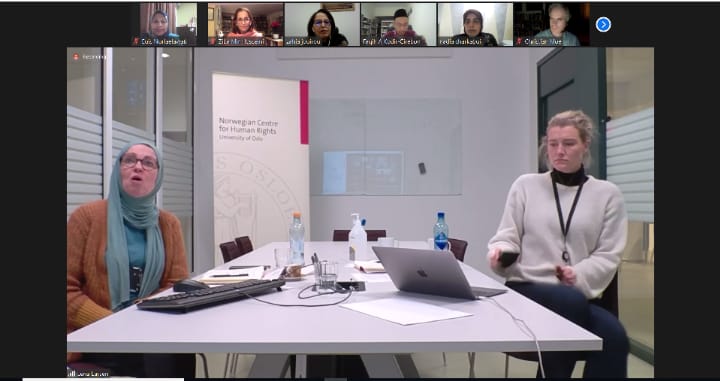
Pelaksanaan Konferensi Internasional via zoom
PERDEBATAN NASAB ANAK DI INDONESIA: ANTARA KESEJAHTERAAN ANAK VIS A VIS PENALARAN KITAB SUCI
Paternitas atau nasab anak muslim di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Aturan yang berkaitan dengan masalah ini paling tidak diatur dalamdua artikel. Yang pertama adalah pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan kawin hamil, yang telah menimbulkan perdebatan tentang keabsahan anak-anak yang lahir dari perkawinan semacam itu, terutama dalam hubungannya dengan waktu melahirkan. Kedua, pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, yang mengatur bahwa garis keturunan anak ditetapkan jika anak lahir dari apa yang disebut “perkawinan resmi” dan anak dianggap tidak sah jika lahir di luar nikah. Sementara banyak cendekiawan Muslim dan praktisi hukum telah memahami bahwa keberadaan pernikahan menjadi sarana untuk afiliasi ayah/paternitas. Di sisi lain terjadi perdebatan tentang apa yang dimaksud dengan pernikahan formal (dalam nikah) dan informal (di luar nikah) dalam kaitannya dengan aturan pencatatan perkawinan dan terwujudnya kesejahteraan anak. Seperti halnya pasal kawin hamil yang menimbulkan perdebatan sengit dan menimbulkan usulan untuk merevisi. Perdebatanini berujung pada usulan uji materil melalui Mahkamah Konstitusi. Hakim kemudian merevisi putusan tersebut sehingga melegitimasi semua anak Muslim di Indonesia tanpa memandang status perkawinan orang tuanya. Revisi ini menyebabkan Majelis Ulama Indonesia mengoreksi keputusan tersebut melalui fatwanya. Sejak saat itu, perdebatanyang lebih keras terjadi di kalangan praktisi hukum.
Pernyataan di atas disampaikan oleh Prof. Euis Nurlaelawati, M.A, Dosen Program Doktor Ilmu Syariah dan Guru Besar Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, pada konferensi internasional yang diselenggarakan olehOslo Coalition on Freedom of Religion and Belief, Norwegian Center for Human Rights, University of Oslo pada tanggal3-4 Desember 2021. Konferensi ini dlaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan mengambil tema: Arah Baru dalam Pemikiran Islam: Perkawinan Di Bawah Umur, dan Kepentingan Terbaik Anak dalam Tradisi Hukum Islam. Beberapa sub tema yang dipaparkan dalam konferensi ini dibahas menggunakan perspektif sejarah, yang meliputi gagasan tentang:
- masa kanak-kanak, kedewasaan dan mayoritas (bulūgh, rushd, tamyīz);
- silsilah, filiasi dan legitimasi (nasab), sebagaimana terstruktur oleh gagasan tentang haram (walad al-zināʾ) dan perwalian, perwalian dan pemeliharaan (wilāya, adāna; kafāladan lainnya pengaturan);
- kepentingan terbaik anak atau konsep serumpun yang dapat ditelusuri dalam tradisi Islam
Selain Prof. Euis Nurlaelawati, konferensi ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai universitas dunia. Mereka adalah:Nora S. Eggen (University of Oslo), Faqihuddin Abdul Kodir(IAIN Sheikh Nurjati Cirebon Indonesia),Zahia Jouirou(Manouba University),Nadia Charkaoui(Jusoor Foundation for Studies, Scientific Research and Training in Morocco), Abdessamad Sbai(Dar El Hadith El Hassania Foundation in Rabat),Youssef Kellam(Al-Qarawiyyin University), dan Saadia Yacoob(Williams College).
Dalam makalahnya, Prof. Euis melihat alasan hukum dan latar belakang sejarah di balik dua aturan utamatentang paternitas tersebut. Halpertama adalah mengobservasi pendapat hukum klasik tentang kawin hamil dan hubungan nasabnya dengan bapak, serta menghubungkannya dengan interpretasi dan pandangan hukum cendekiawan Muslim kontemporer di Indonesia yang secara khusus terlibat dalam proses penetapan perundang-undangan. Disamping itu juga mengkaji latar belakang lahirnya kedua hukum tersebut dan perdebatan di kalangan ulama dan otoritas hukum Islam, baik secara personal maupun institusional.
Berfokus pada landasan hukum Islam dari dua aturan undang-undang, fatwa MUI, dan nilai-nilai filosofis hukum yang terkandung baik dalam putusan maupun fatwa, Prof Euis Nurlaelawati berpendapat bahwa ada pendapat hukum progresif di kalangan ulama hukum klasik, yang pendekatannya dapat digunakan untuk interpretasi kontemporer. Dalam konteks ini, menarik bahwa paternitas anak-anak Muslim di Indonesia tetap menjadi bahan perdebatan serius baik pada tataran normatif maupun praktis. Perdebatan ini tidak hanya bersumber dari preferensi hukum subyektif para ulama dan praktisi hukum, tetapi juga bersumber dari beragamnya interpretasi hukum di antara mereka tentang apa yang dimaksud dengan “kesejahteraan anak” pada khususnya dan maṣlaḥa pada umumnya. Tidak seperti negara-negara Muslim lainnya, seperti Maroko, Indonesia cenderung memiliki keputusan yang singkat dan cukup umum tentang masalah hukum keluarga, termasuk paternitas, meskipun ini mungkin membuka ruang bagi hakim untuk melakukan ijtihad, kesejahteraan anak-anak masih sulit diwujudkan.
